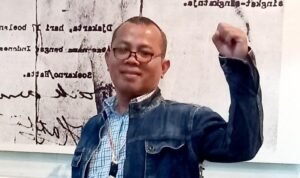Berdentang. Menggelegar. Ide Indonesia Incorporated hadir dengan sejuta harap. Ia bertengger di antara cita-cita ekonomi pancasila dan ancaman korporatisme negara. Ia terucapkan di depan para pengusaha. Benarkah ini solusi kita mengatasi krisis APBN peninggalan pemerintahan sebelumnya? Atau hanya program tanpa agensi seperti yang sudah-sudah? Mari kita telisik dengan pelan dan serius.
Gagasan besar Indonesia Incorporated yang diangkat Presiden Prabowo Subianto merefleksikan ambisi membangun negara dengan paradigma korporasi, seluruh potensi sumber daya, institusi, dan warga negara diarahkan secara terintegrasi untuk mencapai tujuan nasional. Dalam kerangka ekonomi politik Pancasila, gagasan ini bukan sekadar jargon manajerial, melainkan usaha menghidupkan kembali prinsip demokratisasi ekonomi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan produksi dan distribusi sebagai usaha bersama untuk kemakmuran seluruh warga negara.
Secara ideologis, Indonesia Incorporated berupaya menggabungkan efisiensi pasar dengan intervensi strategis negara. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Ekonomi Pancasila adalah sintesis “yang terbaik dari kapitalisme dan sosialisme” yaitu pasar dimanfaatkan untuk inovasi dan kompetisi, sementara negara memastikan pemerataan, perlindungan sektor strategis, dan distribusi manfaat yang adil. Ini sejalan dengan doktrin middle way economics yang berkembang di negara-negara Skandinavia, namun dengan fondasi kultural dan hukum yang khas Indonesia.
Dari sudut apresiasi, pendekatan ini memiliki relevansi strategis. Pertama, ia mengakui pentingnya kedaulatan ekonomi di tengah arus neoliberalisme yang cenderung mengikis kapasitas negara. Kedua, konsep ini membuka ruang sinergi lintas sektor: pemerintah, BUMN, swasta nasional, dan koperasi dapat diposisikan sebagai entitas kolaboratif, bukan kompetitor destruktif. Ketiga, orientasi pada sumber daya domestik mulai dari mineral strategis hingga potensi kelautan menegaskan arah pembangunan berbasis keunggulan komparatif yang dikelola dengan visi jangka panjang.
Namun, dalam perspektif ekonomi politik, kritik dan masukan tak terelakkan. Pertama, gagasan ini berisiko tergelincir ke dalam state corporatism, di mana negara terlalu terpusat mengatur ekonomi layaknya sebuah holding raksasa. Peran itu mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan elite birokratis. Kedua, tanpa kerangka akuntabilitas yang kuat, integrasi nasional dapat menjadi sekadar konsolidasi kekuasaan ekonomi-politik oleh segelintir kelompok, bukan demokratisasi akses dan distribusi. Tentu ini sangat berbahaya karena mampu melahirkan oligarki hitam yang super rakus dan serakah.
Ketiga, terdapat potensi jebakan trickle-down yang memprioritaskan kepentingan korporasi besar dengan asumsi keuntungan akan mengalir ke bawah. Ini harus diwaspadai karena pengalaman di banyak negara menunjukkan efek ini sering gagal terjadi, justru memperlebar ketimpangan dan melemahkan daya saing usaha kecil menengah yang berujung pada kehancuran kelas menengah dan kelas bawah.
Dari sudut pandang kedaulatan ekonomi, Indonesia Incorporated menghadapi dilema mendasar yaitu bagaimana memastikan kontrol penuh atas sektor strategis di tengah ketergantungan tinggi pada modal, teknologi, dan pasar luar negeri. Meski narasinya menekankan pengelolaan sumber daya oleh negara untuk kepentingan warga negara, realitas global memperlihatkan keterikatan pada rantai pasok internasional yang sering kali menempatkan negara berkembang pada posisi tawar rendah. Alih-alih negara menguat, ia justru mengalami swastanisasi negara. Kepala negara (presiden) hanya jadi broker dan makelar dalam bisnis global.
Jika integrasi ekonomi nasional dilakukan tanpa strategi substitusi impor yang sistematis dan penguatan basis industri hulu, maka konsep ini justru bisa memperkuat ketergantungan pada pihak eksternal. Dalam konteks ini, Indonesia Incorporated harus diwaspadai agar tidak menjadi sekadar rebranding dari model pembangunan yang tetap mengandalkan modal asing sebagai penggerak utama. Ingat, modal asing itu ilusi yang sering meninabobokan, bukan obat mujarab buat pasien.
Selain itu, ancaman terhadap kedaulatan ekonomi juga datang dari potensi penetrasi korporasi multinasional ke dalam skema Indonesia Incorporated melalui kemitraan strategis atau aliansi modal. Tanpa regulasi ketat dan keberpihakan jelas terhadap entitas nasional, sinergi yang diharapkan dapat berubah menjadi alih kendali aset vital kepada pihak luar. Pengalaman masa lalu dalam sektor energi, tambang, dan pangan menunjukkan bahwa lemahnya posisi tawar negara sering kali berujung pada kontrak jangka panjang yang merugikan, bahkan mengunci kapasitas negara untuk mengambil alih kendali di kemudian hari.
Oleh karena itu, gagasan ini memerlukan fondasi hukum yang mempertegas bahwa pengelolaan sektor strategis harus berbasis kontrol mayoritas domestik, dengan mekanisme sovereignty safeguard yang tidak bisa dinegosiasikan. Kita pemilik, penguasa, pengelola, dan penarik keuntungan seluas-luasnya. Taka da tafsir lainnya.
Dalam kerangka analisis ekonomi politik berbasis ideologi Pancasila, Indonesia Incorporated tidak boleh direduksi menjadi sekadar manajemen korporasi berskala negara. Pancasila mengandung prinsip kedaulatan rakyat dalam politik dan kedaulatan ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan penguasaan sumber daya alam oleh negara sebagai mandat konstitusional untuk kemakmuran seluruh warga negara, bukan sebagai instrumen akumulasi modal oleh elite atau korporasi besar. Sekali lagi, niat dan paktik harus dari-oleh-untuk kemakmuran seluruh warga negara.
Teori state capitalism (Bremmer, 2010) mengingatkan bahwa ketika negara mengadopsi logika pasar tanpa filter ideologis, ia cenderung menempatkan efisiensi dan akumulasi keuntungan di atas distribusi yang adil. Jika implementasi Indonesia Incorporated terlalu bias pada efisiensi korporatif ala kapitalisme dan mengandalkan asumsi trickle-down, maka sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” akan tereduksi menjadi retorika, bahkan mengkhianatinya.
Tentu, hal ini sekaligus menyimpang dari asas gotong royong ekonomi yang menjadi ciri khas Pancasila. Sebab, orientasi keuntungan yang tidak diimbangi pemerataan berpotensi mengubah negara menjadi aktor pasar pragmatis yang mereduksi fungsi negara sebagai penjaga kepentingan kolektif.
Dalam sejarah ekonomi Pancasila, Bung Hatta (1944) menekankan model koperasi sebagai tulang punggung demokrasi ekonomi. Terjadilah demokratisasi ekonomi (nasionalisasi, restrukturalisasi, rekapitalisasi, redistribusi dan reindustrialisasi). Indonesia Incorporated dalam tafsir Presiden Prabowo perlu memastikan bahwa koperasi dan usaha kecil menengah tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi bagian inti dari arsitektur pembangunan. Jika tidak, “gabungan kapitalisme dan sosialisme” akan berakhir sebagai dominasi model kapitalisme negara yang jauh dari semangat kekeluargaan, bahkan menghancurkannya.
Kesimpulannya, Indonesia Incorporated adalah gagasan besar yang memiliki daya tarik politis dan ideologis. Ia menawarkan narasi alternatif terhadap neoliberalisme, sekaligus berusaha membumikan Pancasila dalam kebijakan ekonomi-politik Indonesia kontemporer. Namun, seperti halnya setiap desain besar, nilainya akan diukur bukan dari retorika atau dokumen kebijakan, melainkan dari kemampuan mewujudkan distribusi kesejahteraan yang nyata, menjaga kedaulatan sumber daya, dan melindungi demokrasi ekonomi dari kooptasi kekuasaan.
Tanpa itu semua, idealisme ini berisiko menjadi sekadar slogan korporatis dalam balutan nasionalisme. Ide ini ibarat “ekonomi menara gading yang cantik namun rapuh secara ideologis.” Akhirnya, ia paradoks pembangunan: megah di permukaan, namun keropos di dalam. Hal tersebut karena tercerabut dari akar Pancasila. Keindahan fasadnya menipu, sementara pondasinya goyah karena mengabaikan keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi yang menjadi ruh ideologi bangsa. Semoga saja tidak.