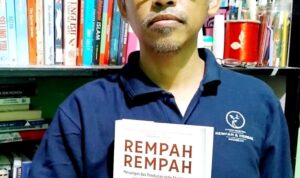Apa itu negara pancasila sebagai rumah besar Ipoleksosbudhankam Indonesia? Inilah salah satu pertanyaan ontologis saat kami melakukan diskusi terbatas di Nusantara Centre, beberapa pekan lalu. Tentu ini penting agar kita punya persamaan persepsi soal titik temu, titik pijak, dan titik tuju dalam bernegara.
Berikut konsensus kami soal jawabannya. Negara pancasila adalah anti-tesa dari negara kapitalisme yang imperialis dan anti-tesa dari negara komunis yang imperialis. Negara pancasila menghibridasi dari kebaikan keduanya plus kebaikan dari peradaban lainnya.
Kita tahu bahwa anak kandung imperialisme purba adalah negara neoliberalisme. Ini adalah wajah mutakhirnya yang berwatak eksploitatif, serakah, anti-kemanusiaan dan anti-ketuhanan. Sistem ini tidak hanya menjajah sumber daya ekonomi negara berkembang, tetapi juga menjadikan warga negaranya sekadar pion dalam skema akumulasi modal tanpa etika, tanpa moral.
Dalam struktur ekonomi ini, lapisan bawah terjerumus dalam sandiwara penderitaan yang terus dipertontonkan tanpa perubahan substansial—ekonomi bawah menjadi panggung sinetron yang menjual ilusi mobilitas sosial. Sementara itu, kelas menengah dijadikan kolam bermain kapital, tempat percobaan kebijakan dan objek manipulasi konsumsi; sedangkan ekonomi atas tetap menjadi aktor utama, pengendali arah, dan peraup hasil dari sistem yang disengaja mengglobal.
Melihat kerusakan struktural dan kultural yang ditimbulkan neoliberalisme tersebut, negara Pancasila hadir bukan sebagai retorika ideologis, melainkan solusi jenius yang mengutamakan keseimbangan antara pasar (swasta), warga negara (koperasi) dan BUMN.
Dari rakhim itu lahirlah ekonomi pancasila yang mengoreksi penyimpangan struktural dengan menempatkan warga negara sebagai subjek ekonomi, bukan sekadar objek statistik. Dalam bingkai ini, demokrasi ekonomi dijalankan melalui keberpihakan pada koperasi, UMKM, serta pengelolaan sumber daya oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran warga.
Sesungguhnya, ekonomi Pancasila tidak menolak pasar, tetapi mengarahkannya agar tidak dikuasai oleh segelintir elite global yang selama ini menjarah atas nama liberalisasi. Inilah jalan tengah kesetimbangan yang masuk akal: rasional, konstitusional, dan membumi.
Fundamen dari sistem ini terletak pada konsep warga-negara dalam negara Pancasila yang menolak paradigma diskriminatif. Ia menghindari penilaian manusia dari garis keturunan, kekuasaan kapital, atau latar belakang tribal semata. Dalam perspektif ini, warga-negara harus hadir berdasarkan tiga status yang menyatu: intelektualis, spiritualis dan sosio-kapitalis.
Pancasila menegaskan pentingnya postur manusia seutuhnya—yakni pribadi yang memiliki daya pikir kritis, jiwa spiritual yang hidup, serta kapasitas sosial yang konstruktif. Setiap manusia menjadi homo sosialis, tanpa kecuali, sehingga memiliki hak dan kewajiban bahkan potensi yang sama untuk berkembang, berpartisipasi, dan mendapatkan tempat dalam tatanan sosial-politik nasional. Kesetaraan ini menjadi landasan etis untuk menciptakan masyarakat yang adil dan tidak terjebak dalam kasta sosial terselubung.
Dengan semangat kesetaraan tersebut, negara Pancasila wajib merumuskan sistem yang aktif dalam menghapus sekat-sekat ketimpangan dan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya. Kesinambungan visi ini terletak pada keberanian negara untuk melampaui sekadar retorika hukum dan bergerak menuju kebijakan yang menjamin distribusi akses yang adil—terhadap pendidikan, pengembangan kapasitas, dan posisi sosial.
Sebab, masyarakat sentosa hanya mungkin lahir jika seluruh warga-negara diberi pijakan yang sama untuk tumbuh sebagai pribadi yang utuh dan produktif. Negara tidak boleh tunduk pada logika kapital, garis trah, atau kuasa mayoritas serta diktator minoritas, melainkan wajib berdiri sebagai penjaga keadilan sosial dalam arti yang sesungguhnya.
Komitmen pada keadilan sosial tersebut bukanlah aspirasi kosong, melainkan bagian dari idealisme bernegara dalam kerangka Pancasila. Ini bukan sekadar konstruksi normatif, tetapi visi historis yang berpijak pada keberlanjutan peradaban Nusantara. Dalam sejarah panjang bangsa ini, nilai-nilai luhur seperti gotong royong, harmoni dengan alam, dan penghormatan terhadap sesama telah menjadi fondasi kolektif yang melampaui sekat suku, agama, dan kelas sosial.
Desain pancadharma—berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, bermusyawarah dan berkeadilan—bukan hanya etika konstitusional, melainkan refleksi nilai-nilai lokal yang telah mengakar sebelum republik ini berdiri. Idealisme ini merekatkan dimensi spiritual, sosial dan ekologis ke dalam satu sistem yang menyatu. Konstruksinya adalah teo-antro-eco sentrism: segitiga kesetimbangan.
Dari sinin menjadi jelas bahwa keberlanjutan bernegara tidak bisa lagi dibangun dengan model developmentalisme semu yang mengorbankan lingkungan dan meminggirkan partisipasi warga-negara. Pancasila mengajarkan bahwa pembangunan harus manusiawi, dialogis, dan berbasis keadilan sosial.
Gotong royong bukan jargon nostalgia, melainkan sistem sosial yang efektif jika diarusutamakan dalam kebijakan publik. Ketika negara menjalankan idealisme Pancadharma secara substantif, maka arah bernegara tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memulihkan relasi manusia dengan sesama dan alam. Inilah peradaban bernegara yang bukan hanya bertahan, tetapi juga berkelanjutan dan bermartabat serta berkemakmuran.